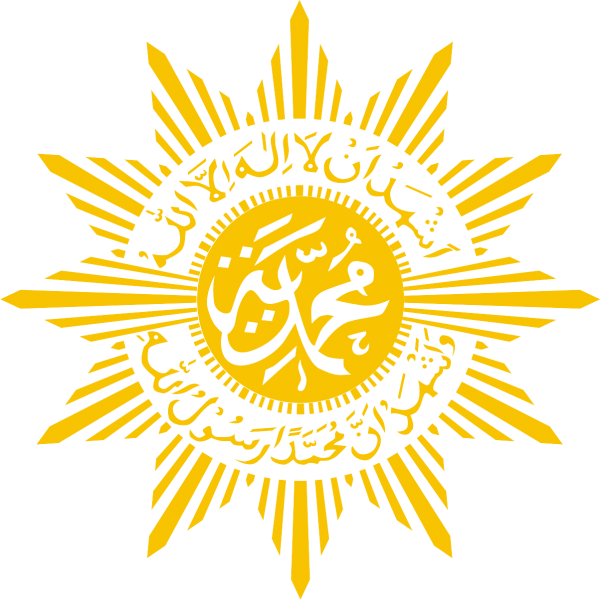Satu Sapi Untuk Lebih dari Tujuh Orang, Kurban atau Sedekah Biasa?
Satu Sapi Untuk Lebih dari Tujuh Orang, Kurban atau Sedekah Biasa?
Pertanyaan:
Assalamu ‘alaikum wr.wb.
Alhamdulillah, di Cabang kami setiap tahun selalu mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ada pengelompokan satu sapi untuk maksimal tujuh orang, dari kelompok A sampai kelompok E (lima kelompok) dengan nominal yang berbeda tiap kelompoknya. Di samping itu ada juga kelompok kolektif tak terbatas (bisa lebih dari tujuh orang untuk satu sapinya). Hal ini dilakukan untuk melatih warga berkurban dan memfasilitasi mereka supaya bisa berkurban tiap tahunnya.
Kami juga melatih peserta didik di AUM dengan iuran untuk membeli hewan kurban (satu sapi lebih dari tujuh orang bahkan ratusan orang). Dalil yang dipakai adalah Rasulullah saw pernah berkurban dua ekor kambing, satu untuk beliau dan keluarga, sedang satunya untuk umat. Salah satu manfaat dengan adanya kolektif tak terbatas ini adalah daging kurban yang dibagikan lebih banyak.
Tapi kemudian ada warga yang mempertanyakan cara ini, takutnya ini tidak diperbolehkan karena bagian dari ibadah dan harus ada tuntunannya. Sedangkan tuntunan yang umum adalah satu unta untuk sembilan orang, satu sapi untuk tujuh orang dan satu kambing untuk satu orang. Pertanyaannya, bolehkah cara itu dilakukan (satu sapi lebih dari tujuh orang), termasuk berkurban atau hanya sedekah biasa? Mohon pencerahannya supaya hati kami bisa lebih mantap.
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
Sunoto, di Sumatera Selatan (Disidangkan pada Jumat, 21 Rabiulakhir 1443 H/26 November 2022 M)
Jawaban:
Wa ‘alaikumus salam wr.wb.
Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan. Masalah serupa sebenarnya pernah ditanyakan dan telah dibahas dalam website Fatwa Tarjih yang diposting pada 28 Januari 2020 dan Majalah Suara Muhammadiyah No. 21 tahun 2006. Namun demikian, tidak menjadi masalah apabila kami harus menjelaskannya kembali.
Kurban secara istilah berarti mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun tuntunan kurban tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya QS. al-Kautsar: 2, QS. al-Hajj: 34-35 dan ayat 36 serta QS. ash-Shaffat: 102-107. Terlebih lagi dalam beberapa sabda Rasulullah saw yang masyhur ditemukan dalam kitab Shahih al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Hukum kurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis Nabi saw,
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَار [رواه مسلم].
Dari Ummu Salamah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal sepuluh Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu [HR. Muslim Nomor 3655].
Seringkali didapati dalam kitab-kitab fikih bahwa satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor lembu untuk maksimal tujuh orang dan satu ekor unta untuk maksimal sepuluh orang atau dikenal dengan istilah kurban kolektif, dengan syarat tetap melihat kondisi hewan yang dikurbankan. Dasarnya adalah hadis sebagai berikut,
عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحَرِ [رواه مسلم].
Dari Jabir (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah saw menyembelih hewan kurban untuk Aisyah seekor lembu pada hari nahar [H.R. Muslim No. 356].
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَحَضَرَ اْلأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةً [رواه الترمذي].
Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan, kemudian datanglah hari raya Adha, lalu kami berpatungan menyembelih lembu untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang [H.R. at-Tirmidzi No. 1501].
Mengenai dalil yang saudara maksudkan sebagai landasan kurban kolektif di Cabang saudara, bahwa Rasulullah saw pernah berkurban dengan dua ekor kambing untuk beliau, keluarga dan umatnya adalah sebagai berikut,
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ [رواه مسلم].
Dari 'Aisyah, (diriwayatkan bahwa) Rasulullah saw pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya ada warna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah: Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari. Kemudian beliau bersabda: Asahlah pisau ini dengan batu. Lantas 'Aisyah melakukan apa yang diperintahkan beliau, setelah diasah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya. Kemudian beliau mengucapkan: Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Kemudian beliau berkurban dengannya [H.R. Muslim No. 1967].
Dalam riwayat lain disebutkan,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى [رواه أبو داود].
Dari Jabir bin Abdullah (diriwayatkan) ia berkata: Aku hadir bersama Rasulullah saw dalam salat Idul Adha di musala (lapangan), maka setelah beliau usai khutbah, beliau turun dari mimbar dan dibawakan di hadapan beliau seekor domba, lalu Rasulullah saw menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri seraya berucap: Bismillah, Allahu Akbar, ini dari Muhammad dan dari umatku yang tidak berkurban [H.R. Abu Dawud No. 2413].
Kedua hadis di atas menjelaskan tentang fi’liyah Rasulullah saw perihal kurban beliau dengan mengatasnamakan keluarga dan umatnya. Akan tetapi, terdapat hadis lain yang secara gamblang menjelaskan bahwa berkurban untuk beberapa orang telah menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah saw, yaitu hadis berikut ini,
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى [رواه الترمذي].
Dari Atha’ bin Yasar mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Anshari perihal kurban di zaman Rasulullah saw, maka jawabnya: Adalah seseorang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan bersama juga memberikannya kepada orang lain. Begitulah hingga manusia gembira dan menjadilah (sunah) seperti yang anda lihat sekarang ini [H.R. at-Tirmidzi No. 1141].
Pengertian keluarga dan umat secara kontekstual pada masa Rasulullah saw dalam redaksi hadis Aisyah di atas perlu ditelaah lebih dalam lagi. Lafal (آلُ) dalam kamus Lisan al-‘Arab menurut Abu Abbas Ahmad bin Yahya disebutkan bahwa terjadi perselisihan dalam memaknai lafal (آلُ النبي). Sebagian kelompok mengatakan keluarga Nabi adalah seluruh pengikutnya, baik kerabat maupun selain kerabat. Sementara sebagian kelompok lainnya menyatakan lafal (آلُ) dan (أَهْلٌ) adalah semakna, yakni (أَهْل البَيْتِ) atau istilah lain keluarga kecil di dalam rumah.
Namun demikian, ditemukan pula dalam kamus Lisan al-‘Arab, lafal (آل مُحَمَّد) dengan dua makna berbeda. Pertama, bermakna kerabat dan para istri Rasulullah saw. Kedua, adalah keluarga dalam makna menganut agama Rasulullah saw yakni Islam. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan bahwa (آل مُحَمَّد) secara kontekstual pada masa Rasulullah saw dalam redaksi hadis ‘Aisyah adalah Rasulullah saw, para istri dan anak-anaknya. Hal ini dikuatkan pula dengan lafal (وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) dalam hadis riwayat at-Tirmidzi Nomor 1141 yang maknanya keluarga di rumah.
Adapun umat yang dimaksud dalam hadis ‘Aisyah dan hadis Jabir ditemukan beberapa penjelasan dalam kamus Lisan al-Arab. Abu Ishaq mengatakan makna umat sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah (2): 213 yakni sekumpulan manusia yang hidup antara Nabi Adam a.s. dan Nabi Nuh a.s. yang awalnya dalam keadaan kafir, kemudian diutuslah Nabi Muhammad saw sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Ada pula yang mengatakan bahwa umat adalah sekelompok manusia mukmin bersama Nabi Nuh a.s. di atas kapal, lalu mereka terpecah-belah setelah adanya kekafiran hingga Allah swt mengutus Nabi-Nya.
Sedang pendapat lain mengatakan bahwa seluruh manusia berada dalam keadaan kafir, lalu Allah swt mengutus Nabi Ibrahim a.s. dan nabi-nabi setelahnya. Abu Manshur mengatakan bahwa umat adalah sekelompok manusia dalam satu agama. Adapun lafal (أُمَّتِى) dalam H.R. Abu Dawud Nomor 2413 di atas merupakan tarkib idafi, yang dalam kaidah usul fikih tergolong kepada lafal ‘am. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa (أُمَّة مُحَمَّدٍ) adalah kaum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pengikutnya, yakni umat sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini yang belum mampu berkurban.
Sehubungan dengan pertanyaan saudara, maka kurban sebagai ibadah yang telah disyariatkan memiliki batasan dan aturan yang telah ditetapkan syariat. Aturan kurban kolektif adalah satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor sapi dan kerbau untuk maksimal tujuh orang serta satu ekor unta untuk maksimal sepuluh orang dengan melihat kondisi hewan masing-masing. Apabila sahibul kurban mampu berkurban satu ekor sapi untuk dirinya atau sahibul kurban mampu berkurban dua ekor kambing atas nama dirinya, maka tidaklah mengapa. Sementara praktik kurban yang biasa dilakukan di Cabang saudara termasuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang terdiri dari beberapa orang bahkan ratusan orang tanpa ikatan keluarga dengan sistem urunan atau iuran perlu ditegaskan lagi akadnya.
Jika ingin menjadi kurban, maka harus definitif siapakah yang menjadi sahibul kurban, sehingga ke depannya harus bergilir semua anggota urunan mendapat haknya berkurban. Situasi tersebut bisa berubah apabila semua anggota urunan menghibahkan urunannya kepada salah satu orang yang menjadi sahibul kurban. Namun jika tidak mau menempuh dua cara di atas, urunan tersebut tidak diakadkan menjadi hewan kurban. Oleh karena itu dapat disimpulkan praktik kurban tersebut merupakan bentuk latihan kurban sebagaimana yang saudara sebutkan dan tergolong sedekah biasa.
Adapun mengenai satu ekor sapi untuk lebih dari tujuh orang, dalam sidang fatwa memang ada pendapat yang diajukan bahwa boleh saja satu ekor sapi untuk kurban kolektif lebih dari tujuh orang, dengan syarat ukuran dan harga sapi tersebut memang di atas rata-rata sapi biasa, sehingga. Hal ini merujuk pada hadis tentang unta jenis jazur yang bisa untuk kolekif 10 orang, bukan unta jenis ba’ir, karena jazur berukuran lebih besar dari pada ba’ir. Dalam hal ini, makna jazur diperluas menjadi hewan kurban yang berukuran besar, termasuk sapi yang ukuran dan harganya di atas rata-rata.
Sebagai contoh, misalnya iuran kurban yang ditetapkan adalah Rp3.000.000,-, maka akan mendapatkan sapi dengan ukuran/harga Rp21.000.000,- untuk kurban kolektif tujuh orang. Sementara untuk membeli sapi dengan ukuran/harga yang lebih besar, misal satu ekor sapi yang lebih besar dengan harga Rp60.000.000,-, kurban kolektif dapat dilakukan oleh 10 orang dengan iuran yang lebih besar pula, yaitu Rp.6.000.000,-. Hal dilakukan antara lain untuk memperoleh kuantitas dan kualitas daging sapi yang lebih baik. Namun demikian, pendapat ini belum mencapai kata mufakat pada sidang Tim Fatwa Agama, sehingga akan dibahas lebih lanjut pada forum yang lain.
Sebagai solusi sementara, apabila tetap ingin melaksanakan kurban sapi secara kolektif tetapi terkumpul lebih dari tujuh orang yang akan iuran, maka kelebihan dari tujuh orang tersebut dapat bergabung dengan tempat atau kelompok lain (baik ikut jamaah lain di suatu masjid atau bergabung dengan tetangga sekitar). Solusi kedua saudara dapat berkurban dengan satu ekor kambing saja.
Berikutnya mengenai doa Nabi Muhammad saw dalam hadis Aisyah di atas yakni lafal (بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِه) tidak berarti satu ekor kambing diperuntukkan bagi seluruh umat, melainkan isyarat bahwa kurban tersebut atas nama Nabi saw, namun pahalanya diharapkan untuk seluruh umatnya. Hal ini wajar sebab Nabi Muhammad saw adalah Nabi bagi seluruh umat yang mengharapkan kebaikan pada umatnya. Ringkasnya bahwa doa tersebut tidak dikaitkan sama sekali dengan jumlah hewan yang dikurbankan Rasulullah saw saat ini sebagaimana tergambar dalam hadis ‘Aisyah di atas.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Sumber: Majalah SM No 10 Tahun 2020
Artikel ini telah tayang di suaramuhammadiyah.id dengan judul: Satu Sapi Untuk Lebih dari Tujuh Orang, Kurban atau Sedekah Biasa?, https://www.suaramuhammadiyah.id/read/satu-sapi-untuk-lebih-dari-tujuh-orang-kurban-atau-sedekah-biasa
 Berkenaan dengan datangnya hari raya pada hari Jum’at, bagaimana pelaksanaan shalat Jum’at pada hari raya tersebut? (PCM Kotagedhe Yogyakarta)
Berkenaan dengan datangnya hari raya pada hari Jum’at, bagaimana pelaksanaan shalat Jum’at pada hari raya tersebut? (PCM Kotagedhe Yogyakarta)
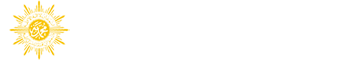
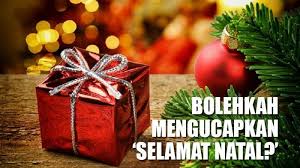

 Satu Sapi Untuk Lebih dari Tujuh Orang, Kurban atau Sedekah Biasa?
Satu Sapi Untuk Lebih dari Tujuh Orang, Kurban atau Sedekah Biasa? Polemik seputar hukum musik masih menjadi sorotan hangat dalam diskusi umat Islam hari-hari ini. Perspektif yang beragam mengenai legalitas musik terus memunculkan pertentangan. Di satu sisi, ada yang memandang bahwa musik secara mutlak haram; sementara di sisi lainnya, ada yang meyakini bahwa musik tidak memiliki batasan hukum yang tegas.
Polemik seputar hukum musik masih menjadi sorotan hangat dalam diskusi umat Islam hari-hari ini. Perspektif yang beragam mengenai legalitas musik terus memunculkan pertentangan. Di satu sisi, ada yang memandang bahwa musik secara mutlak haram; sementara di sisi lainnya, ada yang meyakini bahwa musik tidak memiliki batasan hukum yang tegas.